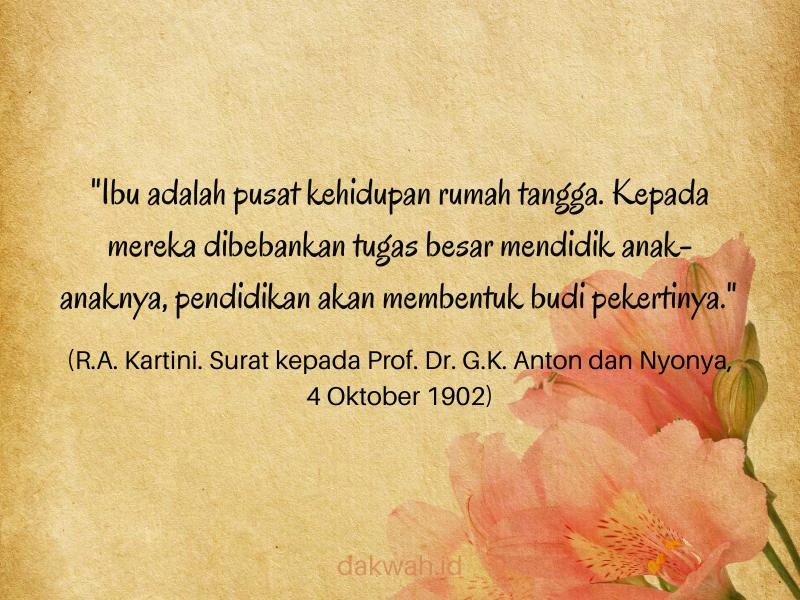Jika kita mau membaca ulang surat-surat Kartini, kalimat demi kalimat, lembar demi lembar, akan kita dapati sebuah perjalanan panjang pemikiran seorang muslimah yang sedang bertumbuh, dari sejak usia remaja hingga ia dewasa. Sosok perempuan yang peka terhadap realitas sosial pada zamannya, juga mencintai al-Quran sebagai kitab suci agamanya.
Setiap bulan April, nama R.A. Kartini digaungkan kembali sebagai ikon perjuangan perempuan Indonesia. Murid-murid perempuan di sekolah berkebaya dan merayakan tanggal 21 sebagai hari khusus untuk mengenangnya.
Lagu “Ibu Kartini” kembali dinyanyikan di mana-mana sebagai bentuk penghormatan atas jasanya.
Hanya saja, dalam wacana kontemporer, Kartini sering justru dijadikan sebagai simbol feminisme. Perjuangannya diklaim sebagai pertentangan atas agama Islam karena telah mengekang perempuan. Bahkan muncul narasi lucu, “jika tanpa feminis, maka anak-anak perempuan Indonesia tidak akan bisa sekolah.”
Narasi semacam ini tentu terlalu menyederhanakan perjuangan seluruh tokoh perempuan di Indonesia dan juga reduksi atas kompleksitas pemikiran Kartini itu sendiri.
Baca juga: Feminisme? Bukan Budayamu!
Jika kita mau membaca ulang surat-surat Kartini. Kalimat demi kalimat. Lembar demi lembar. Akan kita dapati sebuah perjalanan panjang pemikiran seorang muslimah yang sedang bertumbuh, dari sejak usia remaja hingga ia dewasa. Sosok perempuan yang peka terhadap realitas sosial pada zamannya, juga mencintai al-Quran sebagai kitab suci agamanya.
Kartini dan Pendidikan Islam
R.A. Kartini memulai pendidikan formalnya di Europeesche Lagere School (ELS) di Jepara pada tahun 1885, saat berusia sekitar 6 tahun. Sekolah ini merupakan sekolah dasar berbahasa Belanda yang diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan priyayi pribumi.
Di ELS, Kartini belajar membaca, menulis, berhitung, serta bahasa Belanda.
Lingkungan ELS yang memungkinkan Kartini bertemu dengan anak-anak dari keluarga Belanda, menyadarkan Kartini bahwa dalam beberapa aspek, perempuan Eropa hidupnya sangat berbeda dengan nasib perempuan pribumi.
Ia semakin kritis atas adat dan budaya yang timpang terhadap perempuan.
Dalam surat kepada Stella Zeehandelaar, 25 Mei 1899, Kartini menuliskan:
“Oh, alangkah sengsaranya gadis Jawa! Dipingit, dijauhkan dari dunia luar, hanya karena ia seorang perempuan! Kami tidak boleh menuntut ilmu lebih tinggi, karena kata mereka, perempuan cukup tahu dapur, kasur, dan sumur. Adilkah itu?”
Kartini juga mempertanyakan sikap beragama yang tidak melibatkan akal dalam memahami ajarannya. Ia menyayangkan bagaimana ajaran agama yang sejatinya menjunjung keadilan justru sering digunakan untuk membatasi pendidikan perempuan.
“Sering kali saya melihat bagaimana agama dijadikan alasan untuk menekan perempuan. Padahal saya yakin, Tuhan tidak pernah menciptakan agama untuk memperbudak kaum perempuan.” (Surat kepada Rosa Abendanon, 1900).
Sayangnya, yang merespons kegelisahannya hanya kawan-kawan Belandanya. Setelah berhenti dari ELS, Kartini secara otodidak membaca buku-buku dan majalah yang dikirim oleh sahabat-sahabatnya.
Melalui surat-menyurat dengan tokoh-tokoh perempuan Eropa seperti Estelle Zeehandelaar dan Rosa Abendanon, Kartini menyerap berbagai pemikiran tentang emansipasi, keadilan sosial, serta peran perempuan yang tentu sangat eropa sentris.
Meski begitu, Kartini ternyata tidak menelan mentah-mentah yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya tersebut. Ia tidak melupakan jati dirinya sendiri.
Kartini sekalipun tahu ada masalah dalam adat budayanya, namun bukan berarti harus menjadi seperti orang Eropa. Ia bukanlah seorang feminis liberal maupun radikal. Hal ini terlihat dalam corak suratnya juga.
“Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan bagi perempuan, bukan sekali-kali karena kami menginginkan perempuan menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tetapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar bagi perempuan, agar perempuan lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya: menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama.” (Surat kepada Ny. Abendanon, 1 Agustus 1903)
Dalam surat lain kepada Stella, 18 Agustus 1899, Kartini juga menulis,
“Salahkah bila aku ingin perempuan lebih pandai agar menjadi ibu yang lebih baik bagi anak-anaknya?”
Pertanyaan ini menunjukkan arah perjuangan Kartini bukan untuk melawan kodrat sebagai istri dan ibu, tapi untuk menguatkan peran itu dengan bekal ilmu dan pendidikan.
Kartini sendiri sebenarnya sangat tertarik dengan agamanya yaitu Islam. Ia pernah menyatakan bahwa ia sangat ingin memahami al-Quran, namun tidak mengerti isinya karena hanya disampaikan dalam bahasa Arab tanpa penjelasan. Dalam salah satu suratnya, ia menulis,
“Alangkah indahnya isi Kitab Suci itu. Sayang tidak dapat saya mengerti.” (Surat kepada Abendanon, 15 Agustus 1902)
Barulah pada usia 13 tahun, Kartini seperti mendapat angin segar. Ia mengaji ke Kyai Sholeh bin Umar dari Darat (Kyai Sholeh Darat), seorang ulama besar di Semarang.
Kiai Sholeh menulis kitab tafsir berbahasa Jawa, Faidhur Rahman, yang menjadi salah satu karya awal tafsir al-Quran di Nusantara. Kitab tafsir ini ditulis selama 11 bulan, dimulai pada 20 Rajab 1309 H/19 Februari 1892 M dan selesai pada 19 Jumadal Ula 1310 H /9 Desember 1892 M.
Jilid pertamanya terdiri dari 503 halaman, membahas dua surat awal dalam al-Quran, yaitu Surat al-Fatihah dan Surat al-Baqarah.
Artikel Sejarah: Mehrunnisa: Cahaya Dunia dari Takhta Mughal
Pengalaman Kartini berubah saat ia membaca tafsir al-Quran karya Kiai Sholeh Darat. Kartini pun mulai semakin memahami ajaran agamanya. Ia menyadari bahwa berbagai persoalan dalam budaya yang meminggirkan perempuan, bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari pemahaman masyarakat di lingkungannya yang keliru terhadap agamanya.
Dalam momen inilah, Kartini mengaku baru pertama kali bisa merasakan keindahan ajaran Islam yang sesungguhnya. Selama ini, menurutnya, Islam terasa jauh dan tertutup bagi rakyat biasa karena sering kali disampaikan dalam bahasa yang sulit dipahami dan tidak membumi.
Kartini mengatakan, sebagaimana yang dikutip Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya Panggil Aku Kartini Saja,
“Sejak saat itu terbukalah mataku. Indah benar agama Islam itu. Sungguh agama yang suci ….”
Dalam surat kepada Stella Zeehandelaar tertanggal 6 November 1899, Kartini menulis,
“Aku percaya sepenuh-penuhnya kepada Allah. Aku yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan tak akan membiarkan hamba-Nya yang berserah diri kepada-Nya.”
Kartini tidak pernah menolak agama, bahkan justru menjadikannya sumber kekuatan dalam perjuangannya menghadapi keterbatasan sebagai perempuan Jawa kala itu.
Kartini Bukan Feminis
Pandangan feminisme kerap menyerukan kesetaraan absolut antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek, bahkan sampai pada titik menolak peran kodrati dan institusi keluarga. Jika kita baca runtut surat-surat Kartini, ia tidak memosisikan diri pada hal itu.
Ketika Sulamith Firesstone, dalam bukunya The Dialectic of Sex (1970), mengatakan, “Inti dari penindasan terhadap perempuan adalah peran mereka dalam melahirkan dan membesarkan anak.” Kartini justru menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan, karena peran ibu sangat vital dalam membentuk karakter dan budi pekerti anak-anaknya.
“Ibu adalah pusat kehidupan rumah tangga. Kepada mereka dibebankan tugas besar mendidik anak-anaknya, pendidikan akan membentuk budi pekertinya.” (Surat kepada Prof. Dr. G.K. Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1902)
Bahkan Kartini sendiri banyak mengkritik budaya perempuan Eropa. Dalam surat kepada Ny. Ovink-Soer, 12 Januari 1900, Kartini menulis,
“Kami tidak ingin menjadi seperti perempuan Barat yang menanggalkan pakaian kesopanan.”
Ia secara tegas menolak meniru buta model Barat yang menghapus batas-batas moral dan budaya. Kartini ingin perempuan Indonesia maju, namun tetap dalam koridor nilai yang luhur.
Baca juga: Wanita Muslimah Bekerja di Luar Rumah, Apa Syaratnya?
Selain itu, setelah menikah dengan Raden Adipati Joyodiningrat, Kartini justru mendapat dukungan penuh dari suaminya untuk mendirikan Sekolah Kartini di Rembang. Ini membantah klaim bahwa pernikahan adalah pengekangan bagi perempuan. Dalam kasus Kartini, pernikahan justru menjadi pintu pengabdian yang lebih luas.
“… tadinya kami mengira bahwa masyarakat Eropa itu benar-benar satu-satunya yang paling baik, tiada taranya. Maafkan kami, tetapi apakah ibu sendiri menganggap masyarakat Eropa itu sempurna? Dapatkah ibu menyangkal bahwa di balik hal yang indah dalam masyarakat ibu terdapat banyak hal-hal yang sama sekali tidak patut disebut sebagai peradaban?” (Surat kepada Ny. Abendanon, 27 Oktober 1902).
Membaca Kartini sebagai Sebuah Proses Pemikiran
Mengutip suratnya kepada Stella, 26 Oktober 1902, “Saya ingin sekali melihat agama Islam dipahami, bukan sekadar dihafalkan.”
Membaca surat-surat Kartini seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses pemikiran yang sedang berkembang, bukan sebagai pemikiran yang sudah utuh atau final.
Surat-surat Kartini, terutama yang ditulis pada masa remajanya, menunjukkan seorang remaja yang mulai mendapat pemikiran kritis melalui sahabat-sahabat Belandanya.
Seiring waktu, pemikiran Kartini berkembang dan semakin mendalam. Dalam surat-suratnya, Kartini menunjukkan proses pencarian identitas yang lebih kokoh, yang tidak hanya kritis, tetapi juga diwarnai ajaran Islam yang ia pelajari lebih dalam.
Inilah suara Kartini yang sesungguhnya. Seorang muslimah yang mencintai ilmu, menghargai fitrah, dan memperjuangkan pendidikan, bukan pemberontakan. Kartini bukan seorang pejuang supremacy perempuan, tapi seorang pendobrak kebodohan. (M. Wildan Arif Amrulloh/dakwah.id)
Baca juga artikel Pemikiran atau artikel menarik lainnya karya M. Wildan Arif Amrulloh.
Penulis: Muhamad Wildan Arif Amrulloh
Artikel Pemikiran terbaru: